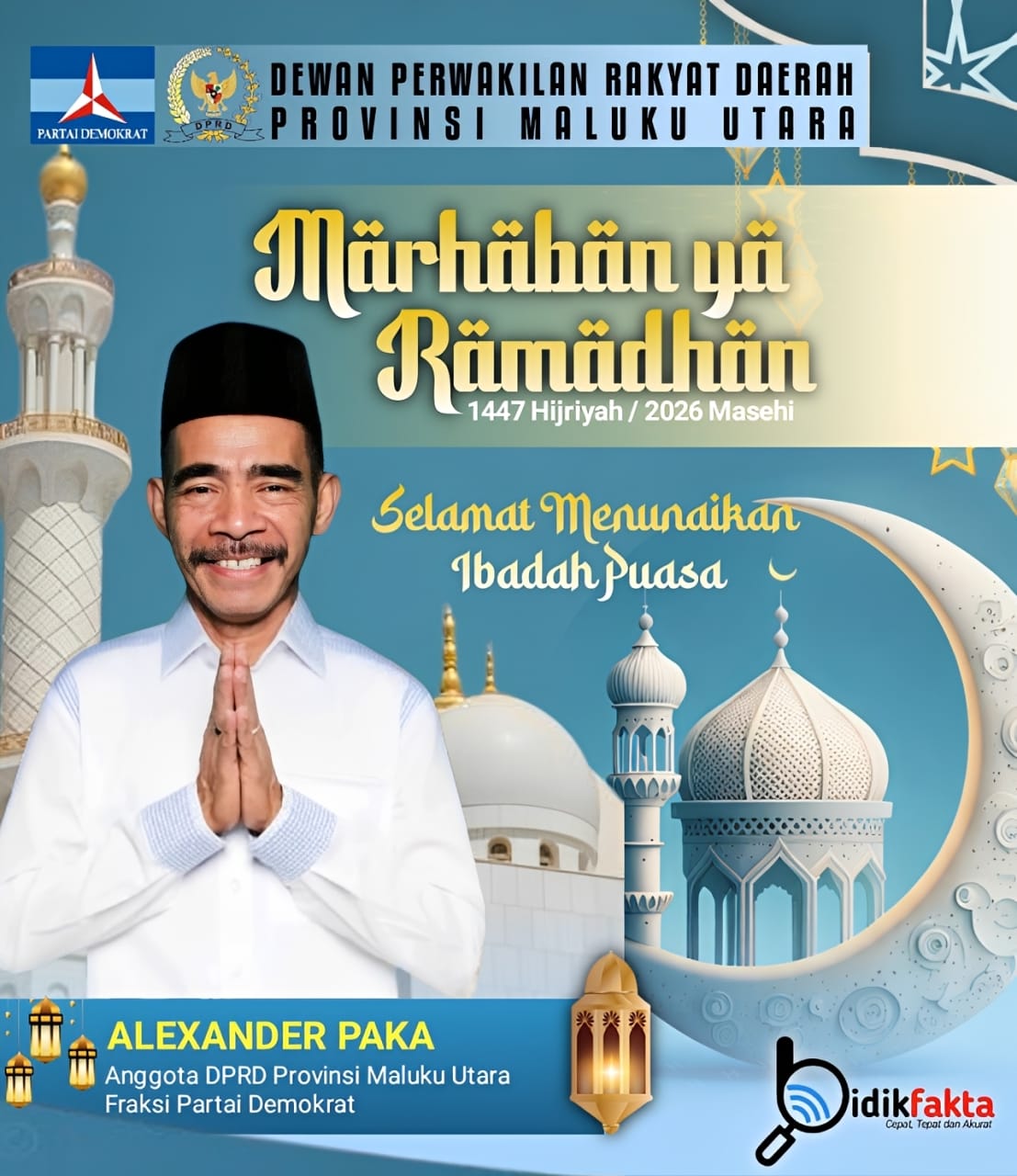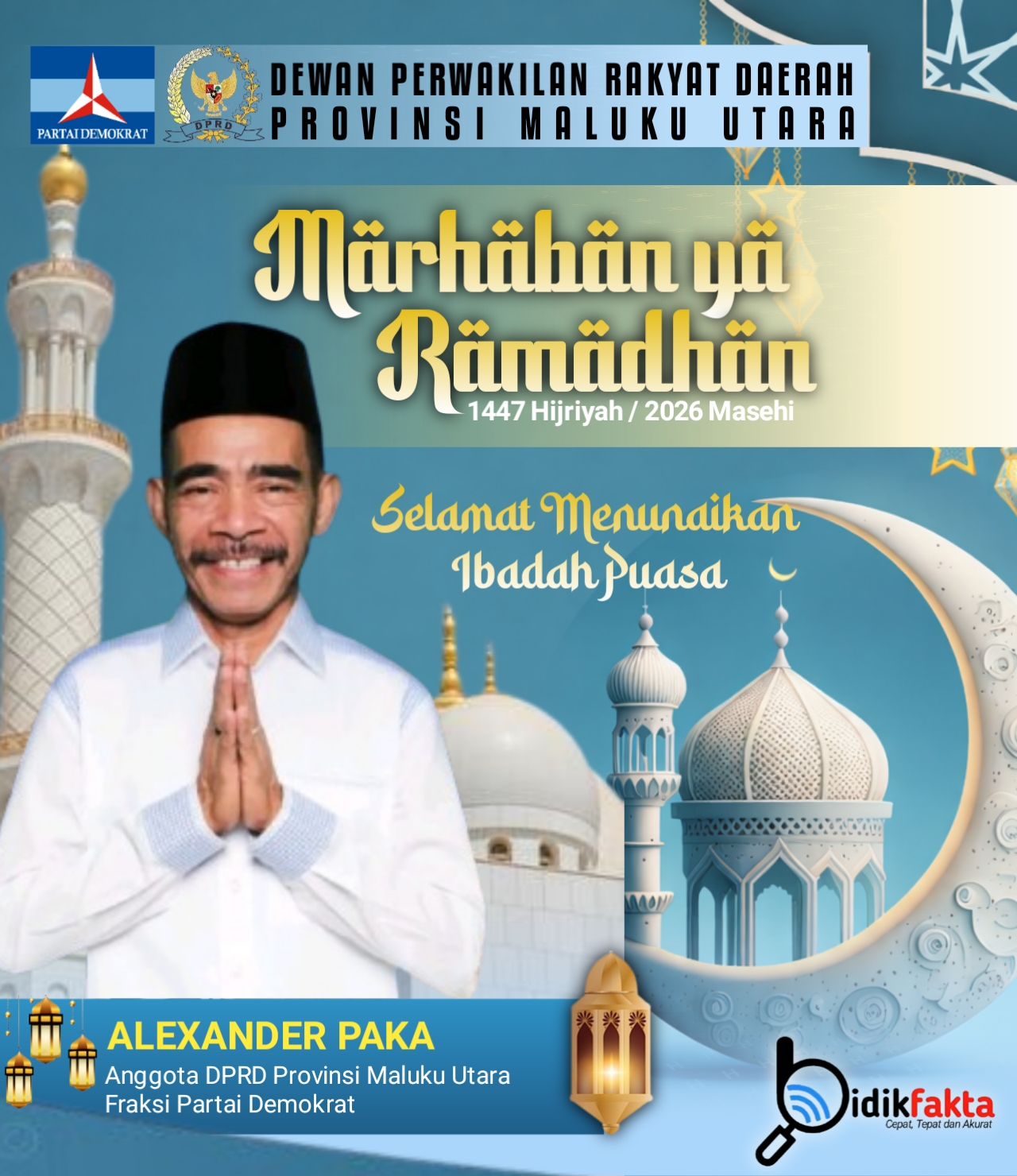Oleh: Mohtar Umasugi
BIDIKFAKTA – Pagi di Kepulauan Sula selalu menawarkan ketenangan yang khas. Secangkir kopi hitam, udara laut yang perlahan menghangat, dan aktivitas warga yang mulai bergerak sederhana. Namun, beberapa waktu terakhir, ketenangan itu kerap terusik oleh kabar-kabar yang membuat hati gelisah. Kabar tentang pemerkosaan, pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penjarahan, dan berbagai bentuk asusila lainnya seakan menjadi tontonan berulang dalam kehidupan sosial kita.
Sebagai bagian dari masyarakat Sula, saya tidak bisa memandang semua itu sebagai peristiwa biasa. Ada rasa cemas yang terus mengendap: mengapa kasus-kasus seperti ini terus muncul, dan mengapa pelakunya datang dari berbagai latar belakang—dari masyarakat kelas bawah hingga mereka yang berpendidikan, memiliki jabatan, bahkan dihormati secara sosial?
Realitas ini menunjukkan bahwa yang kita hadapi bukan sekadar persoalan individu, melainkan akumulasi masalah sosial yang telah lama dibiarkan. Dalam masyarakat kecil dan saling mengenal seperti Kepulauan Sula, kekerasan justru sering lahir dari relasi terdekat. Rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, dalam banyak kasus berubah menjadi ruang sunyi bagi korban. Kedekatan sosial yang tidak disertai kesadaran etis menjelma menjadi celah kekerasan.
Salah satu motif utama dari maraknya kasus tersebut adalah ketimpangan relasi kuasa. Budaya patriarkal yang masih kuat menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, baik dalam rumah tangga maupun ruang sosial. Kekuasaan sebagai suami, orang tua, atau figur yang “dituakan” kerap disalahgunakan. Ketika kuasa tidak dibingkai oleh nilai moral dan tanggung jawab, ia dengan mudah berubah menjadi alat penindasan, terutama terhadap perempuan dan anak.
Di sisi lain, tekanan ekonomi dan kerapuhan sosial juga tidak bisa diabaikan. Keterbatasan lapangan kerja, naik-turunnya daya beli, dan ketimpangan kesejahteraan menciptakan frustrasi kolektif. Dalam kondisi seperti ini, sebagian orang kehilangan kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara sehat. Kekerasan lalu menjadi jalan pintas yang salah sebuah pelampiasan dari beban hidup yang tidak tertangani.
Namun, fakta bahwa pelaku juga berasal dari kalangan terdidik dan kelas atas menegaskan satu hal penting: pendidikan formal dan status sosial tidak otomatis melahirkan kematangan moral. Di Kepulauan Sula, kita belajar pahit bahwa kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan etis hanya akan melahirkan manusia cakap, tetapi miskin nurani. Inilah yang bisa disebut sebagai kemiskinan nilai lebih berbahaya daripada kemiskinan materi.
Motif lain yang memperparah keadaan adalah budaya diam dan normalisasi aib. Banyak kasus kekerasan dan asusila diselesaikan secara tertutup atas nama kehormatan keluarga atau kampung. Korban sering diminta mengalah, berdamai, atau bahkan disalahkan. Praktik ini bukan hanya melukai korban untuk kedua kalinya, tetapi juga memberi ruang aman bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Ketika keadilan dikorbankan demi citra, maka kekerasan akan terus diwariskan.
Tidak kalah penting adalah lemahnya kehadiran hukum yang adil dan tegas. Proses hukum yang lambat, penyelesaian informal tanpa keberpihakan pada korban, serta perlakuan berbeda berdasarkan status sosial menciptakan ketidakpercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, hukum kehilangan daya cegahnya, dan masyarakat perlahan terbiasa hidup berdampingan dengan ketidakadilan.
Semua faktor tersebut berpadu, membentuk sebuah siklus yang berbahaya. Kejahatan terjadi, menjadi tontonan, diperbincangkan sebentar, lalu dilupakan hingga kasus berikutnya muncul. Kita seolah terjebak dalam rutinitas kegelisahan tanpa keberanian kolektif untuk memutus mata rantainya.
Padahal, Kepulauan Sula tidak miskin nilai. Kita memiliki adat, tradisi, dan ajaran agama yang kuat menjunjung martabat manusia. Namun nilai-nilai itu hanya akan hidup jika berani ditegakkan, bukan sekadar diwariskan dalam simbol dan seremonial.
Dalam perspektif Islam, realitas ini seharusnya menjadi cermin muhasabah bersama. Al-Qur’an dengan tegas mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi terjadi karena ulah manusia sendiri (QS. Ar-Rum: 41). Kekerasan, asusila, dan penindasan bukan sekadar pelanggaran sosial, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.” Hadis ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan privat semata, melainkan kegagalan moral yang nyata.
Islam juga menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan martabat manusia sebagai tujuan utama syariat (maqashid syariah). Maka, membiarkan kekerasan berlangsung dengan alasan apa pun bertentangan langsung dengan nilai keadilan dan rahmah yang diajarkan agama.
Catatan kopi pagi dari Sula ini saya tutup dengan harapan sekaligus peringatan. Bahwa tontonan yang meresahkan hari ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jika kita ingin masa depan Sula yang lebih beradab, maka keberanian untuk berubah harus dimulai sekarang dari rumah, dari cara mendidik, dari keberpihakan hukum, dan dari kesediaan kita menempatkan nilai agama bukan hanya di lisan, tetapi dalam laku kehidupan sehari-hari.
Jika tidak, maka kegelisahan ini akan terus diwariskan, dan kopi pagi kita akan selalu terasa pahit oleh kabar-kabar yang sama.